Bebas Akses Kesetaraan Jender
Jalan Panjang Ulama Perempuan Memperjuangkan Kesetaraan
Dengan dukungan dari Co-Impact dan Ashoka, KUPI berikhtiar mempercepat pembangunan ekosistem kesetaraan jender.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F09%2F28%2F7a4eabf4-bb18-45ec-8ab2-718db57e9575_jpg.jpg)
Santri Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (3/9/2024).
Menjelang sore, Selasa (3/9/2024), puluhan santriwati berjalan perlahan menuju asrama masing-masing. Setumpuk kegiatan di Pondok Pesantren (Ponpes) Hasyim Asy’ari, Jepara, Jawa Tengah, menanti mereka sepulang sekolah formal. Tak jarang kesibukan tersebut menyita waktu hingga malam.
Suasana asrama di pesantren tak pernah sepi meski matahari telah terbenam. Santri perempuan saling berbagi tugas. Berbagai kegiatan hampir berlangsung paralel, mulai dari mengaji hingga memasak. Baru pukul 22.00 WIB, semua kesibukan santri harus berhenti. Waktunya tiba untuk istirahat karena mereka harus bangun kembali menjelang subuh.
Setidaknya dua dekade lalu, pemandangan ini bisa jadi tak terlihat. Santriwati terkurung dan menerima hak yang tak setara dengan laki-laki. Misal, santriwati mendapatkan jam malam dan kegiatan yang lebih terbatas.
Pengasuh Ponpes Hasyim Asy’ari, Hindun Anisah, menjelaskan, pesantren memang banyak terkungkung dalam pemikiran agama tradisional yang menempatkan posisi sosial perempuan berbeda dengan laki-laki. Perubahan sosial dan pendidikan kesetaraan jender perlu ditanamkan secara perlahan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F09%2F28%2Fa8394adc-c790-4594-b7c1-783cabec1c60_jpg.jpg)
Pengasuh Ponpes Hasyim Asy’ari, Hindun Anisah, Selasa (3/9/2024).
Sejak pindah ke Jepara dari Yogyakarta pada 2003, tekadnya kukuh untuk berjuang agar santri perempuan ditempatkan setara dengan laki-laki. Tiap santriwati harus mendapatkan akses, hak, dan peluang yang sama. Penilaian murni mengacu pada kapasitas dan kompetensi seseorang.
”Perubahan datang dari hal kecil. Dulu, kan, biasanya kalau di pesantren itu santri laki-laki boleh keluyuran sampai malam. Sementara yang perempuan dibatasi. Perlakuannya berbeda. Pembatasan jam malam harus berlaku untuk keduanya,” tutur Hindun.
Memang sengaja kami kenalkan agar memengaruhi perspektif para santri. Mengonstruksi nilai-nilai keadilan jender itu penting.
Tak berhenti di situ, kegiatan-kegiatan Ponpes Hasyim Asy’ari yang selama ini hanya terbuka untuk santri laki-laki kini juga berlaku bagi perempuan. Di antaranya pengajian, kajian, termasuk kegiatan di luar pesantren, seperti olahraga, jurnalistik, dan berbagai ekstrakurikuler lain. Ini mengapa setiap kegiatan di Ponpes Hasyim Asy’ari selalu diikuti santri laki-laki dan perempuan.
Perjuangan awal kesetaraan jender di pesantren paling mudah dimulai lewat ranah praksis. Para pendidik konsisten mengenalkan jejak tokoh agama perempuan, termasuk dari kalangan internal ke santri Ponpes Hasyim Asy’ari agar menjadi inspirasi. Ini perlu ditempuh sebelum masuk ke pendidikan teoretis.
Baca juga: Ulama Perempuan Berperan Mencegah Ekstremisme
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F09%2F28%2F7a4eabf4-bb18-45ec-8ab2-718db57e9575_jpg.jpg)
Santri berjalan perlahan menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Hasyim Asy’ari, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (3/9/2024).
Hal serupa diungkapkan oleh Pimpinan Ponpes Tarbiyatul Islam (PPTI) Al Falah, Salatiga, Siti Rofiah. Di tengah masyarakat, kepemimpinan perempuan di pesantren kerap masih dipertanyakan. Upaya keras dibutuhkan untuk mengubah pola pikir tradisional tersebut.
Langkah pertama adalah memperbanyak kegiatan yang menampilkan pengurus pesantren perempuan. Materi-materi pendidikan seputar nilai-nilai jender pun ikut dimasukkan dalam kurikulum. Santriwati didorong untuk belajar kitab, misalnya, yang berisi kehidupan istri Nabi Muhammad SAW. Kisahnya menceritakan perempuan yang berdaya dan mumpuni.
”Memang sengaja kami kenalkan agar memengaruhi perspektif para santri. Mengonstruksi nilai-nilai keadilan jender itu penting,” ujarnya.
Penolakan
Langkah Hindun sebagai ulama perempuan yang memperjuangkan kesetaraan jender tak berlangsung mulus. Penolakan dari masyarakat, ulama laki-laki, bahkan perempuan lain menerpa. Salah satunya datang dari orangtua santri yang mempertanyakan mengapa putrinya didorong berkuliah di tempat jauh.
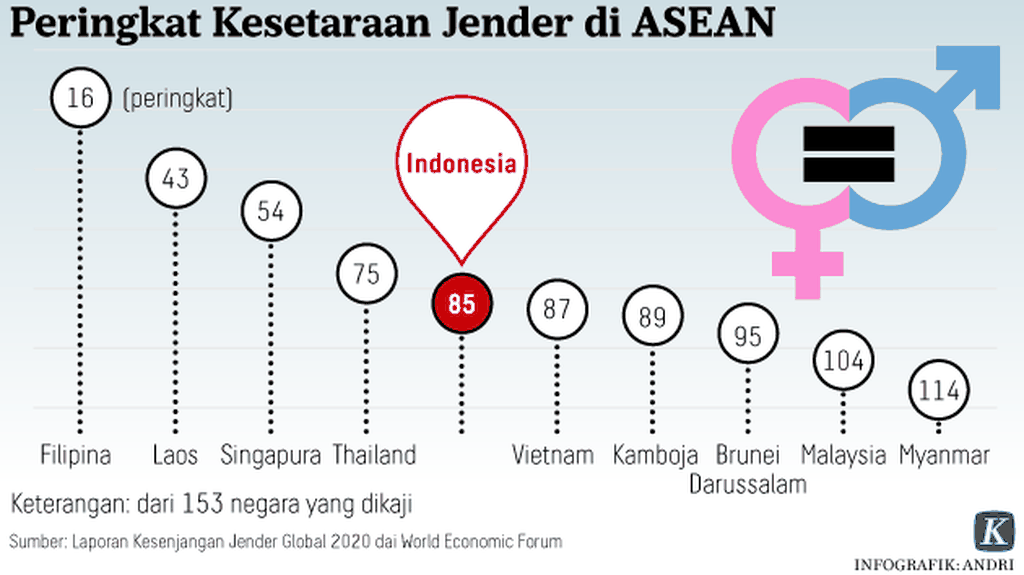
Bagaimana tidak. Pemikiran masyarakat Jepara saat itu masih memandang perempuan tak perlu berkuliah dan berkegiatan yang jauh. Cukup tingkat SMA/MA saja. Kalau ingin berkuliah, paling jauh di Semarang. Sementara Ponpes Hasyim Asy’ari mendorong santriwati untuk mengeksplorasi kapasitasnya.
”Silakan (para santri) kuliah di Jakarta, Yogyakarta, bahkan luar negeri. Kami buka aksesnya, edukasinya, pilihan beasiswanya,” ucap Hindun.
Selain pola pikir masyarakat tradisional, ulama laki-laki tampak terusik dengan pemikiran Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan itu. Hindun menduga pendidikan kesetaraan jender mengganggu zona nyaman otoritas keagamaan yang didominasi laki-laki. Ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan struktur sosial di mana hak-hak perempuan dikebiri.
”Dari sisi otoritas keagamaan, di sini (Jepara) masih tetap awal-awal, jadi ya tetap (dominasi) laki-laki. Jadi, misalnya ngaji, ya, masih laki-laki. Saya pernah sampai dituduh ulama liberal. Tapi saya tunjukkan syariat mana yang dilanggar? Apa sih yang sebenarnya dituduhkan? Karena tak ditemukan, perlahan mereka hilang,” tuturnya.
Baca juga: Gerakan Perempuan Hadir dalam Setiap Babak Sejarah, Menyelamatkan Indonesia

Perwakilan anak-anak muda mendiskusikan permasalahan yang ditemui di sekitar mereka dalam acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2 di Pondok Pesantren Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (26/11/2022).
Menurut aktivis perempuan kelahiran Yogyakarta itu, penolakan cenderung muncul dari masyarakat dan ulama generasi tua. Penduduk usia muda, khususnya para santri lebih terbuka dengan hal baru seperti kesetaraan jender. Secara perlahan, mereka mulai sadar ada yang salah.
Sang suami yang juga pengasuh Ponpes Hasyim Asy’ari, Nuruddin Amin, turut mendukung gagasan Hindun untuk menerapkan pendidikan kesetaraan jender. Ia pun tak menampik penolakan yang muncul dari ulama tradisional.
Pasca-KUPI, seluruh peserta, misalnya kampus, membentuk komunitas hingga meneliti bersama isu-isu terkait. Pesantren-pesantren juga sama, pengurus langsung konsolidasi dan buat kegiatan bersama seperti kajian dan event.
”Tantangan itu terutama datang dari kalangan kiai yang konvensional. Mereka khawatir terhadap wacana kesetaraan jender itu lahir dari liberalisme,” ucapnya.
Pemikiran tokoh agama tradisional, menurut Nuruddin yang akrab disapa Gus Nung itu, wajar karena jarang bersentuhan dengan topik seputar ulama perempuan. Padahal, kesetaraan jender dalam Islam dianut dari penafsiran Al Quran secara murni.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F09%2F28%2F2bbb32db-5e0a-4899-9900-35c1a1c99912_jpg.jpg)
Suami Hindun Anisah yang juga pengasuh Ponpes Hasyim Asy’ari, Nuruddin Amin, menunjukkan sejumlah buku tentang kesetaraan jender yang bebas diakses para santri di Ponpes Hasyim Asy’ari, Senin (2/9/2024).
Untuk itu, gagasan kesetaraan jender harus masif disuarakan. Di Ponpes Hasyim Asy’ari, santri bebas mengakses pemikiran-pemikiran seputar kesetaraan jender lewat buku-buku yang memuat tafsir dan fikih. Salah satunya Qiraah mubadalah yang merupakan penafsiran gagasan Faqihuddin Abdul Kodir soal keterhubungan laki-laki dan perempuan.
Menurut Siti Rofiah, resistensi publik muncul akibat gerakan yang frontal. Secara perlahan, isu-isu kesetaraan jender mulai menerapkan strategi yang berbeda, sesuai dengan struktur dan kultur kedaerahan. Kajian-kajian mulai menggugat perspektif keagamaan yang tak memihak terhadap perempuan.
Islam, lanjutnya, membuka banyak ruang dialog untuk membahas fikih dan tafsir terhadap Al Quran. Namun, kultur patriarkis menutup hal itu. ”Dalam Islam banyak fikih yang seolah tak bisa digugat. Padahal, Islam membuka banyak sekali ruang dialog. Banyak ruang, tapi nilai patriarki yang besar menutup itu,” tambah Siti.
Berkembang pesat
Ulama perempuan yang memperjuangkan kesetaraan jender tak dilakukan secara individu. Kehadiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) kian mengakselerasi gerakan penyadaran masif di publik. KUPI yang telah digelar dua kali, di Cirebon pada 2017 dan di Jepara pada 2022, menghasilkan sejumlah fatwa yang menjadi platform perjuangan komunitas organik itu.
Baca juga: KUPI Jadi Inspirasi Gerakan Kaum Perempuan di Negara Muslim
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F11%2F26%2F1e5b12ea-29a8-42c1-917b-2306134e9bac_jpg.jpg)
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2 di Pondok Pesantren Hasyim Asyari, Jepara, Jawa Tengah, resmi ditutup, Sabtu (26/11/2022), dan melahirkan delapan rekomendasi atau fatwa KUPI.
Tak hanya perempuan pimpinan pondok pesantren, akademisi, peneliti, guru, aktivis, bahkan pelajar pun ikut berperan aktif. KUPI menjadi forum pertemuan para tokoh agama berperspektif kesetaraan jender. Berbagai diskursus tak lagi tabu untuk dibahas. Mereka kompak tak ingin direpresi dalam tafsir tunggal agama yang menyatakan perempuan adalah subyek kedua, bahkan kerap hanya dijadikan obyek.
Siti Rofiah, yang juga merupakan pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menuturkan, kehadiran KUPI menegaskan gerakan ulama perempuan yang berjuang untuk kesetaraan jender tak berlangsung individualistis. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dengan masalah kedaerahan yang berbeda-beda.
Bagi akademisi, KUPI membuka ruang konsolidasi elemen-elemen intra dan antarkampus. Mereka tinggal mengimplementasikan fatwa dan hasil kesepakatan lewat kegiatan kampus seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), diskursus terbuka, bahkan penyusunan kurikulum pengajaran.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F11%2F23%2Fa145b577-ce8f-4d79-b4f5-0cea78dedebd_jpg.jpg)
Peserta yang telibat diskusi saat mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2 di Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (23/11/2022).
”Pasca-KUPI, seluruh peserta, misalnya kampus, membentuk komunitas hingga meneliti bersama isu-isu terkait. Pesantren-pesantren juga sama, pengurus langsung konsolidasi dan buat kegiatan bersama seperti kajian dan event,” ucap Siti.
Di sisi lain, Hindun Anisah pun melihat KUPI sebagai wadah untuk bertemu dan bertukar pikiran antarulama perempuan. Tiap peserta bisa melihat penerimaan isu kesetaraan jender di sejumlah daerah. Capaiannya tak dipatok target-target tertentu.
Dia mencontohkan, perjuangan kesetaraan jender di Jepara dan Aceh bakal berbeda. Penerimaan dan keterbukaan masyarakat terhadap perspektif jender di Aceh sudah bisa dianggap sebagai pencapaian besar. Ini tak bisa dibandingkan dengan Pulau Jawa yang secara umum lebih egaliter.
Meskipun begitu, para peserta KUPI yang berasal dari berbagai latar belakang bergerak sesuai kemampuan masing-masing. Guru lewat pengajaran, peneliti lewat publikasi, aktivis lewat advokasi, pengacara lewat pengawalan isu hukum keadilan jender, dan sebagainya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F11%2F23%2Fec006a89-3da7-4cab-9bd4-ead580e5ca3e_jpg.jpg)
Peserta perwakilan sejumlah negara dari Asia, Afrika, Arab, Eropa dan Amerika hadir mengikuti Kongres Ulama Perempuan 2 di Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (23/11/2022).
Lagi pula, KUPI mendefinisikan keulamaan tidak harus bersifat individu. Ulama bisa berisi sekelompok orang yang bersama-sama menyikapi dan menginterpretasikan ayat Al Quran dengan perspektif keadilan hakiki bagi laki-laki dan perempuan.
Sembari mempertahankan independensi, KUPI pun mengupayakan penguatan pemahaman masyarakat pada kesetaraan jender dengan membuka peluang kolaborasi sebesar-besarnya. Salah satunya lewat kerja sama dan pendanaan dari sejumlah pihak, termasuk dukungan dari Co-Impact dan Ashoka. Langkah ini terus mendorong pembangunan ekosistem jender yang setara agar lebih cepat lagi.
Perjuangan para ulama perempuan itu kini belum usai. Jalan panjang syiar kesetaraan jender harus terus disuarakan. Jangan sampai gerakan kembali ke titik nol karena konservatisme agama maupun kebijakan politik.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 2 dengan judul "Ikhtiar Ulama Perempuan Gapai Kesetaraan".
Baca Epaper Kompas





