Fenomenologi Pemilu 2024
Pengalaman secara kronologis pembelajaran dan pembentukan nilai utama kepemiluan perlu direfleksikan lagi.

Pengalaman pemilu perlu dikomunikasikan, terutama Pilpres 2024, untuk mengetahui apakah sudah memenuhi harapan. Sebab, telah muncul pandangan pemilu secara normatif terselenggara, tetapi kehilangan legitimasi. Pandangan ini sebenarnya reduksionistik dan deterministik karena hanya merujuk persepsi ethical determinist yang menyatakan problem etik telah menggerogoti Pemilu 2024.
Sejak Reformasi, pemilu terselenggara, tumbuh, dan berkembang menjadi pemilihan serentak. Pemilihan anggota legislatif (pileg) sudah dilaksanakan sebanyak lima kali (1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019). Pilpres diselenggarakan empat kali (2004, 2009, 2014, dan 2019). Baru pada 2019 dilaksanakan bersamaan pemilu lima surat suara untuk memilih presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.
Pemilu masa Reformasi merupakan kelanjutan dari pemilu legislatif zaman Orde Baru hasil penataan partai politik, yang dilaksanakan sebanyak lima kali (1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997). Pemilu zaman Orde Baru membuahkan asas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Kemudian, pada pemilu era Reformasi ditambahkan prinsip jurdil (jujur dan adil).
Apakah setelah memiliki kekayaan pengalaman, prinsip jujur dan adil mudah terdistorsi persoalan etik yang mengiringi pencalonan presiden dan wakil presiden lalu? Atau sebaliknya, persoalan yang muncul makin memperkuat kinerja pemilu jujur dan adil?
Baca juga: Merindukan Pemilu nan Jujur dan Adil
Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemudian memasuki era reformasi saat ini, dapat dideskripsikan pergeseran praktik pemilu. Peserta pemilu zaman Soeharto hanya tiga partai atau organisasi politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Penyederhanaan partai itu, ditempatkan dalam kerangka stabilitas politik, sebagai sebuah prasyarat mutlak meraih pertumbuhan ekonomi. Proses pemilu difokuskan untuk memperoleh legitimasi melalui metode mobilisasi.
Proses mobilisasi membentuk pemahaman bahwa asas umum sebagai ”pesta” yang meliputi pemilih sebanyak-banyaknya. Salah satu ukuran keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Hal ini masih berlaku hingga kini.
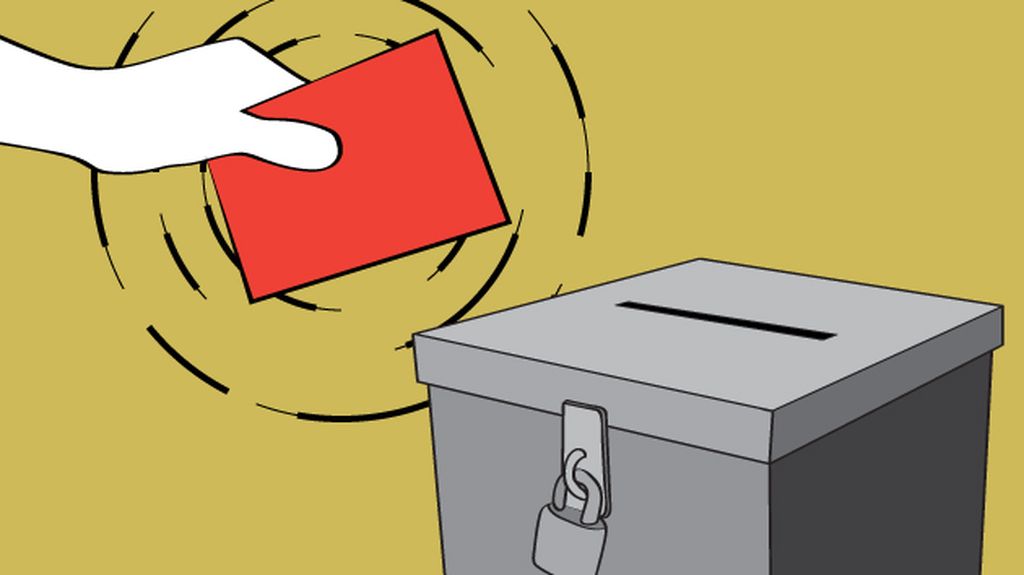
Ideologi stabilitas politik, membatasi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi, bahkan menekan bentuk-bentuk partisipasi lain yang menjadi tugas pokok partai politik dan diemban civil society. Konsekuensinya, reformasi ibarat ”pintu bendungan” yang telah sekian lama tertutup lalu dibuka, dan airnya tumpah ruah.
Keterbukaan dan kebebasan politik telah mendorong partisipasi semakin meluas. Terutama, mengubah penyelenggaraan pemilu tidak bersifat mobilisasi, tetapi arena kompetisi, dan membangun partisipasi pemilih otonom. Ibarat sebuah permainan, sportivitas menjadi prasyaratnya.
Partai politik bertambah, simpul civil society menjamur, berkembang kelompok kecil baru bermodalkan keahlian teknologi informasi dan komunikasi yang menyuarakan kepentingan umum sebagai proses pematangan masyarakat warga yang mandiri. Semua berjalan perlahan, tetapi terus-menerus.
Tindakan kepemiluan yang bijaksana mampu mengurangi ketidakpastian, ketidakjelasan, dan mampu memberi respons pada segala situasi.
Dalam artikel Kusumawati & Arawindha diuraikan kata fenomenologi pertama kali disampaikan oleh Hegel melalui bukunya, Phenomenology of the Spirit (1870), yang mengemukakan pola evolusioner pengetahuan dalam format kesadaran yang paling sederhana sampai rumit (Kholifah & Suyadnya, 2018).
Dengan demikian, pengetahuan mengenai prinsip pemilu yang jujur dan adil merupakan proses kreasi, penciptaan, dan aktivitas kepemiluan. Bukan struktur, tetapi ditentukan oleh ”perilaku-perilaku kepemiluan bijaksana yang bertukaran (intersubjectivity)”.
Penyelenggara tidak bereaksi pada lingkungan (eksternal), tetapi menciptakan melalui interaksi, dan penciptaan makna pemilu. Penyesuaian dengan lingkungan diperankan sesuai rasionalitas asas-asas yang dimilikinya.
Oleh sebab itu, perlu direfleksikan kembali pengalaman secara kronologis pembelajaran dan pembentukan nilai utama kepemiluan. Sejarah Reformasi dilahirkan oleh para pemikir yang berjuang di zaman Orde Baru.

Presiden Abdurrahman Wahid telah menancapkan tonggak sejarah bermakna dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Pasal 8 bahwa ”Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan”.
Dalam penjelasannya diuraikan, ”independen dan non-partisan artinya bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau pemerintah.”
Nilai independen dan non-partisan melandasi prinsip jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, pengetahuan yang ditemukan bahwa asas jujur dan adil itu bukan representasi pemilu, tetapi diwakili dari perilaku dan tindakan bijaksana.
Tindakan kepemiluan yang bijaksana mampu mengurangi ketidakpastian, ketidakjelasan, dan mampu memberi respons pada segala situasi. Pada masa Husni Kamil Manik, Muhammad, dan Jimly Asshiddiqie (2012-2017), dapat disebut sebagai tonggak berikutnya dalam merawat dan menampilkan perilaku kepemiluan sesuai asas-asasnya.
Baca juga: Serius Mengurus Pemilu
Ramlan Surbakti dalam opini ”Manipulasi Hukum dan Malapraktik Pemilu” memberikan catatan keras. Fenomena malapraktik kepemiluan berkonsekuensi pada integrasi nasional (Kompas, 10 Januari 2024).
Pengalaman bermakna dimiliki, catatan kritis telah dipaparkan terbuka, begitu pula stok informasi, norma, dan nilai tentang cara institusi merespons segala situasi tersedia. Maka, pada Rabu, 14 Februari 2024, yaitu hari pemungutan dan penghitungan suara dapat dilakukan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Dengan demikian, sejarah pemilu kembali terukir dengan tinta emas.
Nanang Trenggono, Dosen Komunikasi Politik Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung