Memilih Apa atau Siapa?
”Demos” dan ”kratein” terjaga jika warga saling menghormati nilai satu sama lain. Sulitnya, kesombongan memengaruhi.

Ilustrasi/Supriyanto
Soekarno dan Hatta pernah menunjukkan diri sebagai pribadi-pribadi yang mau melayani rakyat dalam pendirian banyak bagian bangsa. Mereka dulu disebut ”Saudara Soekarno” atau ”Saudara Hatta”; bukan ”Yang Mulia” seperti satu-dua ”orang hebat” di Republik Indonesia masa kini.
Tiga orang besar, seperti Ki Hadjar Dewantara, Sutan Sjahrir, ataupun Sayuti Melik, memiliki jarak keyakinan, tetapi mereka berpadu hati.
Melayani rakyat
Rengasdengklok memaparkan perundingan (bukan saling memaki) yang mendekatkan sikap beda menjadi searah untuk dipilih dalam memproklamasikan Republik. Mereka melayani aneka ideologi dengan beda posisi politis.
Mereka mau mengatasi bedanya posisi Jong Java dari Jong Celebes serta memilih mau saling melayani dan saling menyatukan pendirian ”satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa”. Kita dapat bertanya: seberapa relakah orang-orang yang kini mengaku sebagai calon pemuka negara 2024 melayani kebutuhan rakyat dan bukannya mau memerintah rakyat untuk mengikuti pendirian mereka?
Beberapa unsur memerintahkan rakyat untuk tunduk pada pendirian mereka sampai memakai argumen keras: kalau kamu berotak, ikutlah saya! Kalau tidak, ya, ”kamu goblok”.
Sejauh ini bahkan banyak dari warga negara kita yang mengiklankan diri; bukannya menyediakan diri untuk melayani pendirian rakyat.
Mereka pada Pemilu 2024 ini meminta didudukkan ”di atas”, yaitu di suatu posisi memerintah. Seperti dahulu rakyat jelata memandang raja atau sultan, sebagaimana pemilik negara dan ”tuan/penguasa besar” dalam kerajaan.
Mereka meminta dipilih menjadi penguasa dalam negara, bukan melayani rakyat.
Betapa cara itu berlainan dengan orientasi bernegara sejak abad-abad terakhir. Banyak di antara kita melupakan orientasi bernegara, yang pegangannya adalah melayani hasrat seluruh rakyat yang menjunjung tinggi kebebasan, persaudaraan, dan kesamarataan.
Banyak di antara kita melupakan orientasi bernegara, yang pegangannya adalah melayani hasrat seluruh rakyat yang menjunjung tinggi kebebasan, persaudaraan, dan kesamarataan.
Sementara itu, di media, banyak yang mengaku mendasarkan pendiriannya pada ”kebebasan, persaudaraan, dan kesamarataan”, tetapi dalam pelbagai diskusi terus-menerus terdengar nada ”menindas lawan debat, memusuhi teman diskusi, menempatkan diri di atas lawan”, tanpa cukup mengemukakan argumen rasional, yang sama rata dan diwarnai kebebasan pikiran.
Rupanya cara pandang itu dipasang oleh cara yang dipakai beberapa pengurus dan penyurvei negara, yang baru akhir-akhir ini diciptakan oleh sistem politik, yang disangkutpautkan dengan erat pada cara pikir yang dibangun oleh cara menjadikan rakyat sebagai ”massa yang mengikuti mesin politik dan hitungan kuantitatif”. Ada yang seolah-olah menekankan kebebasan dalam berargumentasi.
Setiap warga masyarakat dikatakan mempunyai kedudukan yang sama untuk dikemukakan dan diperjuangkan.
Di situlah lembaga peradilan, dari yang terendah dalam keluarga dan kampung sampai dengan yang tertinggi dalam negara, mendapat kedudukan serupa. Sementara media memperlihatkan betapa banyak cara untuk menyuramkan makna keadilan.
Selanjutnya, warna dasar persaudaraan dipakai, tetapi kadang kala lebih dikaitkan dengan ”saudara sedarah”. Bukan saling memperlakukan saudara seperti dalam Kongres Pemuda dan di masa proklamasi ketika Soekarno dan Hatta pun disebut hanya ”saudara”, tidak usah ”Yang Mulia”.
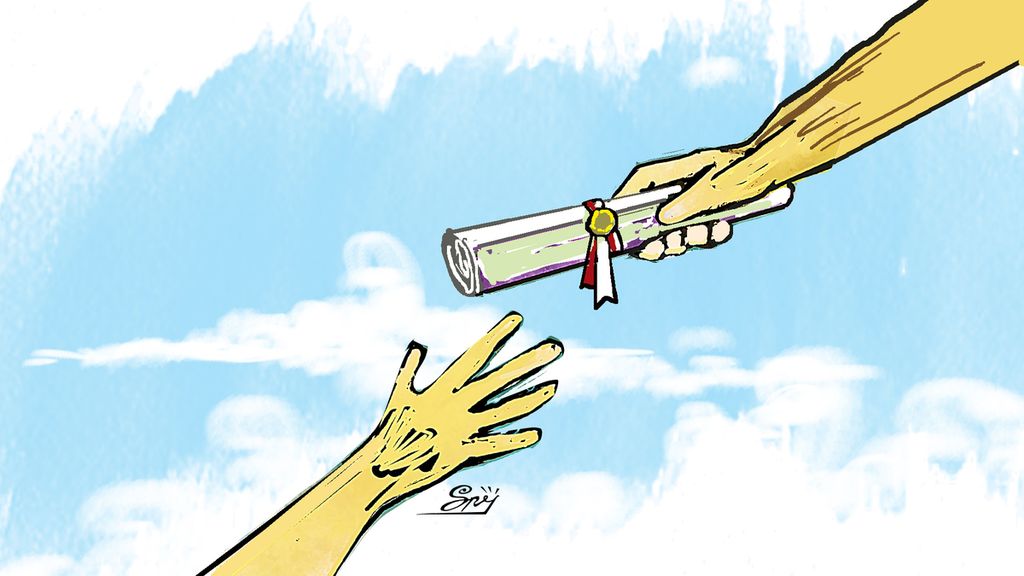
Keserupaan dalam melangkah, memikir, dan merasakan dalam masyarakat di masa proklamasi itu bertumpu pada keyakinan bahwa warga memiliki relasi seperti saudari/saudara. Relasi dasarnya adalah cinta kasih; bukan persaingan kuasa, haus kuasa, dan rebutan harta.
Dengan sikap batin itulah, setiap saudara mau menjaga hidup saudara kandung dan tidak rela ataupun mau melukai atau menyakiti serta (ikut serta) membunuh saudari/saudara—dengan menutup-nutupi kebenaran, keadilan, seraya menyalahgunakan ”rahasia negara” walau melanggar ”jangan membunuh, jangan menciptakan kebenaran semu”.
Itulah sebabnya, semakin banyak daerah menolak hukuman mati. Kerap kali sila kelima Pancasila diajukan sebagai perwujudan kesamarataan.
Dengan pendirian dasar tersebut, semua warga dalam pelbagai keluarga, masyarakat, dan pribadi mana pun resminya diakui kesamaan nilai diri dan hak hidup serta berperan dalam masyarakat (dan tak ada keluarga yang diberi kewenangan khusus, hanya atas dasar kemiripan kartu penduduknya).
Jalan bersama saling melayani
Kewenangan manusiawi untuk diakui oleh undang-undang dasar secara sama mengakibatkan siapa pun mau menjaga kebersamaan. Sebab, semua sudah lama memang mau jalan bersama, seperti perkembangan sejak Kebangkitan Nasional, Kongres Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan.
Tak seorang pun dalam setiap bagian bangsa memiliki ”lebih banyak hak untuk hidup” dibandingkan dengan yang lainnya. Maka, juga tak ada yang bisa merebut hak sesama untuk bergerak, tidur, hidup dan mengambil kedudukan, sampai kebebasan bergerak atau berkembang.
Dapat timbul pertanyaan, kalau demikian, dalam hidup bersama, di mana dapat ditemukan interaksi sehingga warga dapat saling menjaga dengan demokratis? Demos dan kratein terjaga jika semua warga saling menghormati nilai satu sama lain. Sulitnya adalah, kesombongan memengaruhi.
Maka, diakuilah iman akan ”Dia, satu-satunya yang menciptakan dan menyelenggarakan hidup bersama kita”. Tuhan Yang Maha Esa, itu saja yang kita akui dalam proklamasi kemerdekaan kita.
Lalu, apa yang dapat kita lakukan dalam hidup bersama kalau penguasanya adalah Tuhan kita? Kepada masing-masing dari kita, keluarga kita, kelompok kita dalam jalan bersama, kita menjanjikan untuk saling melayani dan bukannya saling menguasai dalam kewargaan bersama kita.
Cara melayani dapat melalui perasaan, pemikiran, penggarapan langkah (teknologi dan persiapan sebelumnya).
Oleh sebab itu, istilah ”pemerintah” perlu digeser menjadi ”pelayanan satu sama lain”. Cara yang sekarang ditampakkan adalah ”rebutan kekuasaan”. Padahal, seseorang di masa kini, jika mau melamar pekerjaan, biasanya mengambil sikap: ”Saya seperti ini, saya bisa membantu apa kepada kamu.” Hal ini sebagaimana dilakukan oleh para penerima tamu/telepon pada kantor mana pun.
Rupanya kita perlu kembali ke keluarga-keluarga kita yang umum: ”untuk kerjaan bersama kita lima tahun yang akan datang, saya bisa melayani apa kepada bangsa kita”. Bukan: saya boleh menguasai apa?
Itu wujud khas kita. Servio, Ergo Sum: adaku itu untuk melayani (bukan untuk menguasai).
Baca juga: Demokrasi Bisa Bunuh Diri: Pelajaran dari Pemilu Dunia
BS MardiatmadjaRohaniawan