Kekerasan Verbal dalam Kampanye Pilpres
Semakin mendekati ”deadline” coblosan pilpres, peternakan kekerasan verbal kian berkembang biak.

Jejak digital menggoreskan fakta debat calon presiden (capres) diwarnai dengan kekerasan verbal. Benarkah demikian? Hal itu tampak terlihat dan terdengar dari ucapan mereka saat menjawab pertanyaan dari moderator. Selain itu, juga tampak nyata ketika para kandidat capres mengomentari ataupun menyanggah pernyataan dari lawan debatnya.
Penampakan visual kandidat capres yang berhasil membantai pernyataan verbal dari capres lawannya secara psikologis terbukti terlihat merasa puas dan bahagia. Apalagi saat pernyataan, jawaban, dan sanggahannya disunting sedemikian rupa menjadi status media sosial yang berujung viral.
Hasilnya? Mereka bangga atas ungkapan kekerasan verbal yang sudah dilakukannya. Sementara korban kekerasan verbal harus menahan malu dan terpuruk di sudut panggung debat capres.
Kekerasan verbal dalam kampanye pilpres dipahami sebagai siasat propaganda capres berikut pendukungnya yang dijejalkan di dalam gerbong komunikasi politik.
Proses komunikasi politik itu dibingkai dalam wujud kampanye hitam dengan tujuan merendahkan, bahkan mematikan lawan politiknya. Sementara tujuan utamanya adalah meningkatkan statistik elektabilitas kandidat capres. Ujungnya, mereka berharap lonjakan suara lewat kertas suara yang dicoblos warga masyarakat.
Semakin mendekati deadline coblosan pilpres, peternakan kekerasan verbal kian berkembang biak.
Kata berkuasa
Semakin mendekati deadline coblosan pilpres, peternakan kekerasan verbal kian berkembang biak. Di sudut lainnya, kata, diksi, dan frasa menjadi penguasa tunggal dalam menyebarluaskan kekerasan verbal.
Lalu, siapa yang menyebarluaskan kekerasan verbal itu? Siapa pun yang terlibat aktif di dalam perhelatan pesta demokrasi pilpres!
Dari sini dapat dipahami manakala fenomena perang asimetris kampanye pilpres dengan amunisi kekerasan verbal menjadi semakin lezat. Apalagi, saat kekerasan verbal diamplifikasikan dan dikumandangkan warganet. Apa wujudnya? Berupa ujaran kebencian, ”nyinyirisme”, hoaks, disinformasi, dan miskomunikasi.
Dampak psikologisnya? Siapa pun berpotensi mengalami luka batin. Hal itu terlihat jelas ketika produsen kekerasan verbal sengaja mengapitalisasi dan memolitisasinya. Target utamanya, apa lagi kalau bukan mematikan karakter capres dan parpol pengusungnya yang dianggap sebagai lawan politik.
Dalam perspektif budaya visual, drama kekerasan verbal sengaja dipanggungkan lewat media sosial dan ruang publik. Arah fokusnya? Tentu untuk mempertontonkan drama kekerasan verbal dalam kampanye pilpres. Karena itulah, bangunan narasi dan goresan storytelling sengaja dirangkai menjadi representasi kata sebagai penguasa tunggal.

Tugas politiknya? Digunakan sebagai kemasan bahasa komunikasi politik untuk saling menyindir antar-para pihak yang terlibat aktif di arena kampanye pilpres. Secara konotatif, tafsir representasi kata berkuasa direkatkan makna upaya saling menyindir dalam konteks gerbong kampanye pilpres.
Teks kekerasan verbal dalam kemasan bahasa komunikasi politik, oleh mereka, secara sengaja disemburkan secara masif dan terstruktur kepada seteru politiknya.
Dari rekam jejak digital, kata berkuasa dalam wadah bahasa komunikasi politik kekerasan verbal, antara lain: ”... samsul, belimbing sayur, #SoloBukanGibran, #AsalBukanPrabowo, ”drakor”, ”pengkhianat”, ”nirmoralitas, niretika”, ”halalkan segala cara”, ”bocah ingusan, belum berpengalaman”, ”mahkamah keluarga”, ”politik dinasti”, ”anak pak lurah”, ”bu lurah vs emak banteng”.
Selain itu: ”pertarungan perasaan”, ”supremasi hukum jeblok”, ”pemerintah gagal”, ”matinya demokrasi”, ”omon-omon, omong doang, pinter omong praktiknya kosong …’’.
Semua representasi kata berkuasa dalam taferil bahasa komunikasi politik saling menyindir di atas selalu didengungkan pelakon kekerasan verbal. Aktivasinya dilakukan saat mereka menjalankan proses komunikasi politik di ruang publik ataupun jagat maya, yang dikumandangkan lewat medsos.
Representasi kata berkuasa dalam taferil bahasa komunikasi politik kekerasan verbal dalam propaganda capres dimitoskan sebagai senjata pembunuh lawan politiknya.
Representasi kata berkuasa dalam taferil bahasa komunikasi politik kekerasan verbal dalam propaganda capres dimitoskan sebagai senjata pembunuh lawan politiknya. Keberadaannya secara otomatis dicatat algoritma media sosial sebagai jejak peradaban politik modern era budaya digital.
Hal itu diyakini menjadi catatan sejarah milik tim pemenangan capres dan partai politik pengusung bakal capres saat menjalankan komunikasi politik kekerasan verbal di ruang publik dan media sosial.
Ketika kata, diksi, dan frasa diberi ruang untuk berkuasa sekaligus menjadi penguasa tunggal, pada titik ini mereka merasa diberi mandat untuk membasmi lawan politiknya. Tujuannya? Tentu saja untuk menunjukkan kedigdayaan jenama politik milik parpol sekaligus personal branding politik yang powerful milik capres peserta kontestasi Pilpres 2024.
Konten propaganda politik
Masalahnya kemudian, mengapa mereka memilih kekerasan verbal sebagai konten propaganda politik di media sosial dan ruang publik?
Bagi mereka, tentu hal itu dianggap peristiwa biasa. Pola pembiasaan seperti itu didasari kebenaran mitos budaya kekerasan verbal dalam konteks komunikasi politik di ruang publik dan media sosial.
Benarkah siasat kekerasan verbal wajib dijalankan? Keberadaan mitos budaya kekerasan verbal semestinya tidak dijadikan fondasi, apalagi jati diri capres, partai pengusung, tim pemenangan, dan relawan.
Sudah saatnya mereka mengusung proses komunikasi politik empatik saat menjalankan kampanye capres.
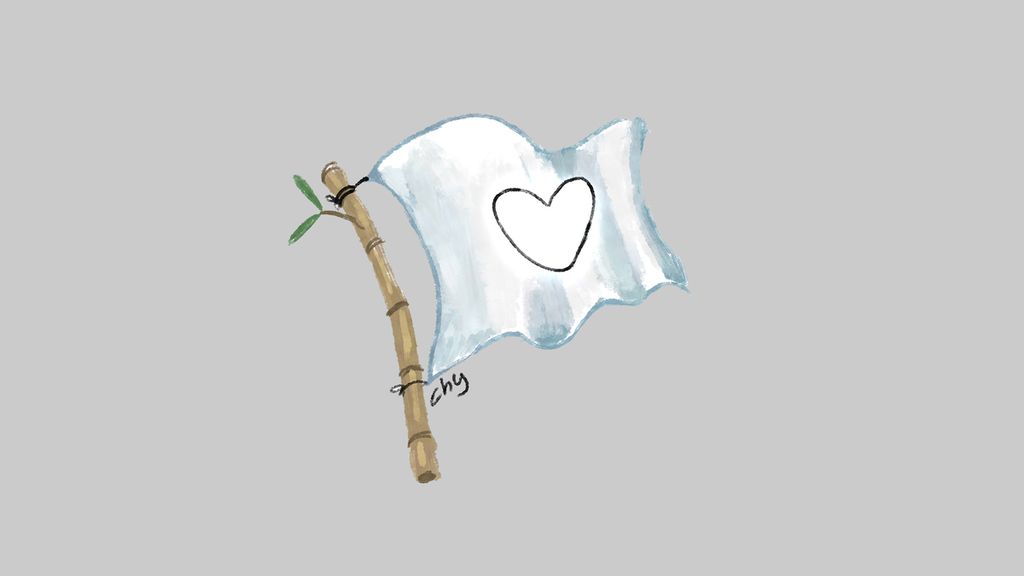
Proses kontestasi pilpres semestinya berlangsung dengan mengedepankan identitas capres Indonesia yang selaras dengan kelima sila Pancasila. Bukan capres yang kemaruk dengan kekuasaan lewat propaganda kampanye hitam dengan storytelling kekerasan verbal.
Realitas sosial mencatat dengan tinta merah konten propaganda politik capres kemaruk kekuasaan lewat kampanye hitam dengan storytelling kekerasan verbal. Catatan itu dapat dibaca sebagai narasi orientasi berpikir capres bersama tim pemenangan, relawan dan partai pengusung, bahwa masih bergerak di seputar wilayah perut.
Artinya, mereka berorientasi untuk memuaskan libido lapar dan haus kekuasaan. Bukan berhikmat menjadi pelindung, pembimbing, dan pelayanan rakyat Indonesia.
Baca juga : Pentingnya Kritik dan Godaan Demagogi
Baca juga : Demagog dan Manipulasi Emosi Publik
Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSRD ISI Yogyakarta